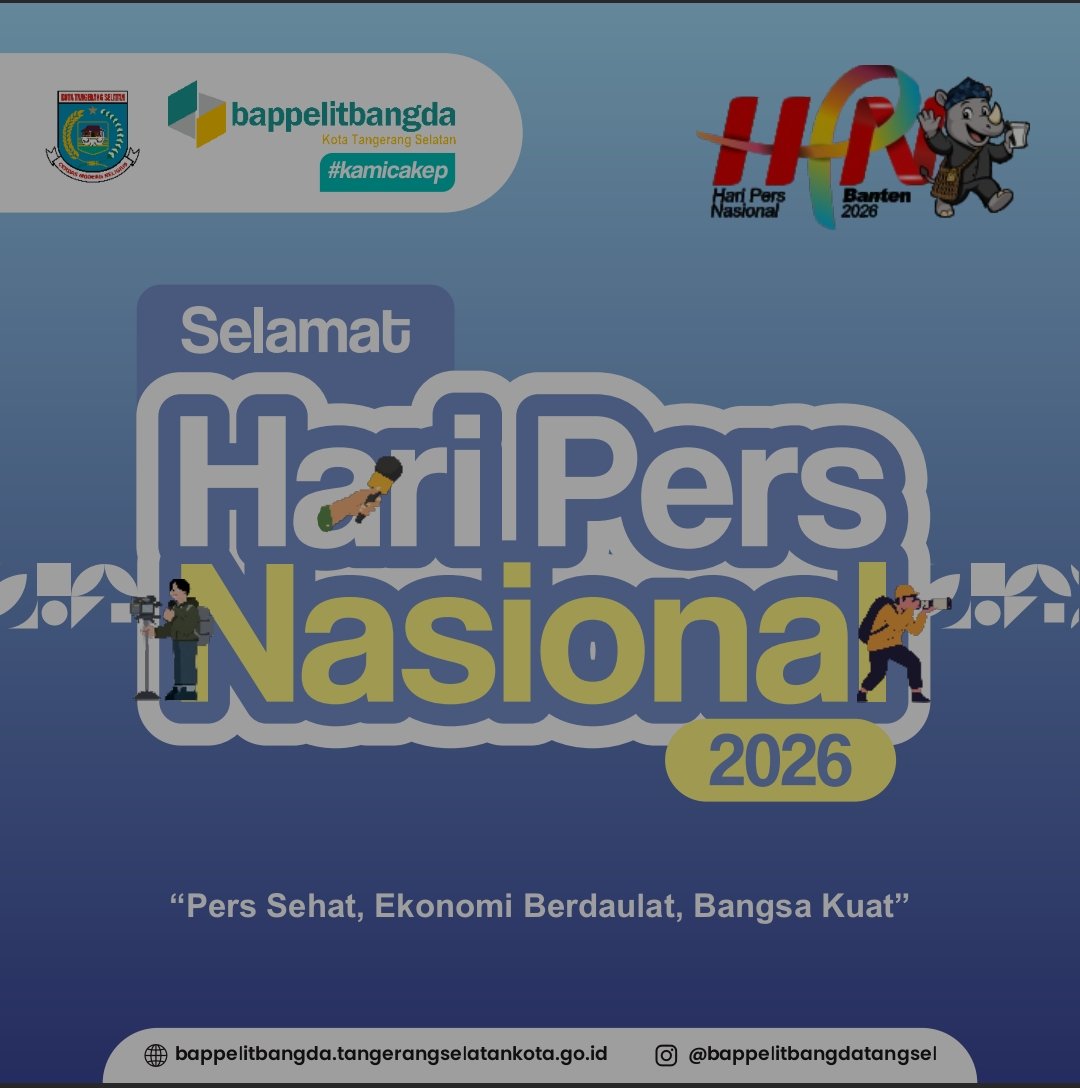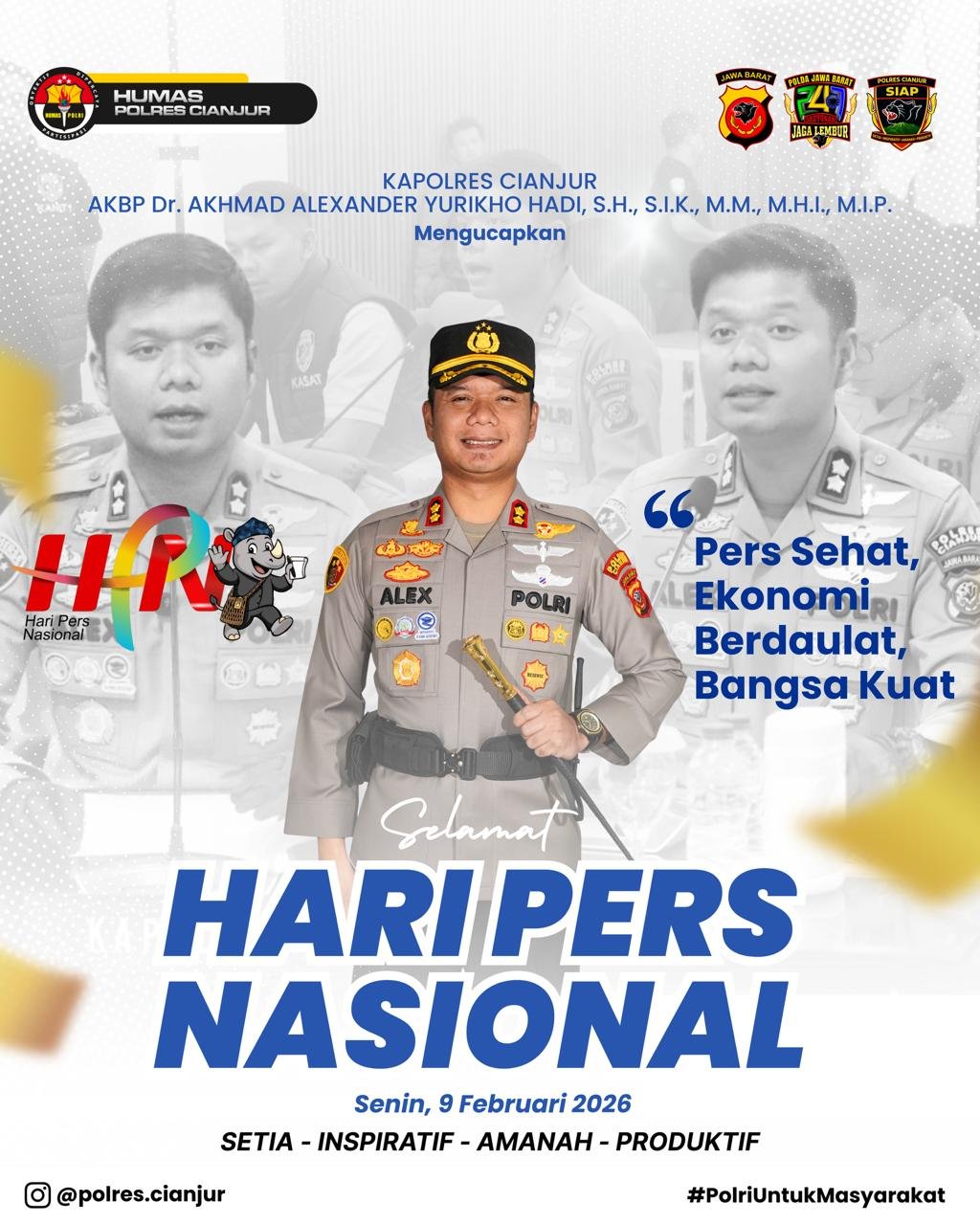Inung Tuak Kraeng Toe Teing Ami Mendi, Oleh Eddy Ngganggus

Suatu waktu ketika burung gagak akan punah dari Manggarai dan itu merupakan kali terakhir ia akan hidup di sana, ia bertengger di atas sebuah ranting pohon tua yang selama ini menjadi rumah tempat tinggalnya.
Ia ingin meninggalkan kesannya kepada manusia dengan beberapa untaian kata sebelum ia pamit pergi dan takan kembali lagi. Ia ingin meninggalkan sketsa nasibnya selama bersama manusia yang pernah hidup bersamanya.
Sketsa rasa itu ia ungkapkan dalam bentuk nyanyian dengan syair lagu kurang lebih seperti berikut. “inung tuak kraeng toe teing ami mendi, ami mendim o kesa weong ge”
Ia memparalelismekan nasib dirinya nya sebagai mendi di hadapan tuannya kraeng dengan tuaknya. Tuak yang dalam budaya manusia Manggarai adalah minuman elit & eksclusive.
Alam tempat ia (gagak) dan kaumnya tinggal adalah tempat paling elit dan nyaman (sedap seperti tuak) dan yang exclusive, tidak lagi di punyainya karena semuanya oleh manusia telah di tebang untuk di nikmati sendiri oleh manusia.
Bandingkan dengan filosofi Manggarai yang memandang “puar” sebagai anak rona. Karena dari puar itu berasal molas poco sebagai haju siri bongkok mbaru gendang. Menjadi sangat pantas kita memperlakukan puar dan luasan alam semestanya sebagai tempat tinggal dan hidup sesama kita yang lain.
Kata almarhum Paus Frasiskus, manusia bukanlah pusat hidup (anthroposentris) , tetapi masih ada makhluk lain juga. Bersama makhluk lain yang ada di semesta Manggarai.
Maka oleh Paus Fransiskus di serukan agar ada pertobatan ekologis. Teser poka puar pinanaeng, hentikan eksplotasi sumber daya alam tanpa kendali. Agar jangan sampai terjadi seperti burung gagak yang sudah “pamit” dari hutan Manggarai.
Eme inung tuak kraeng neko hemong r’oeng do, neka inung hanang koe. Kalau mengeksplorasi alam jangan terlalu egois, sisakan buat makluk lain yang habitatnya ada di sana.
Kontributor : Bino Maot